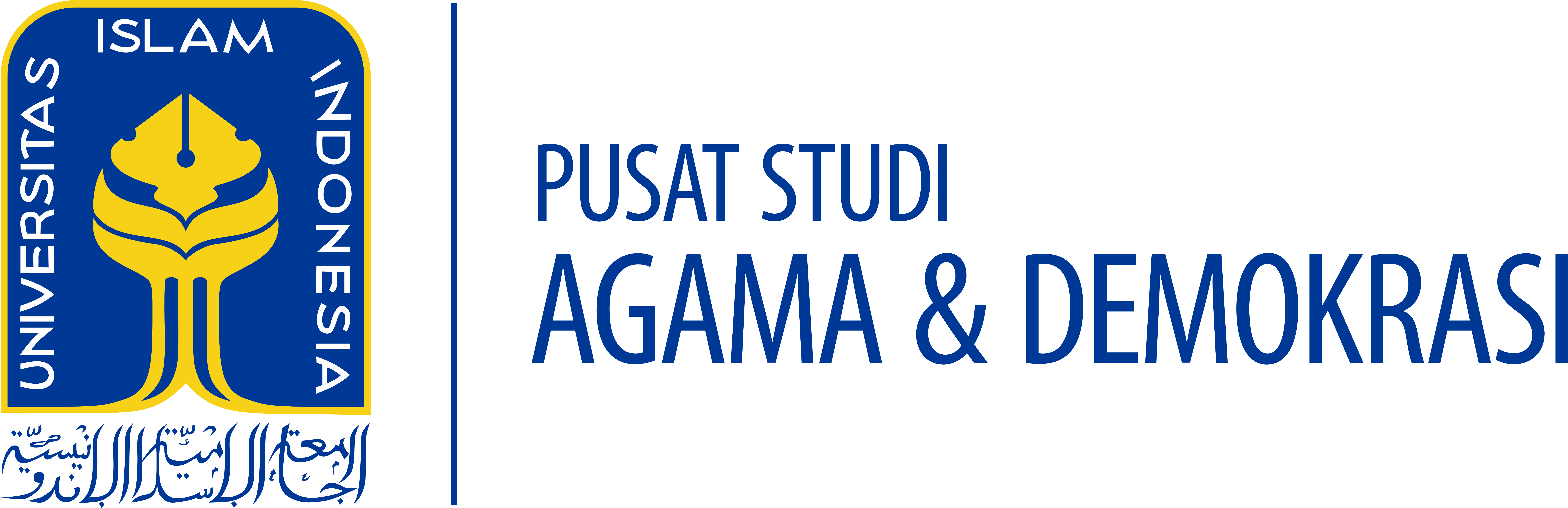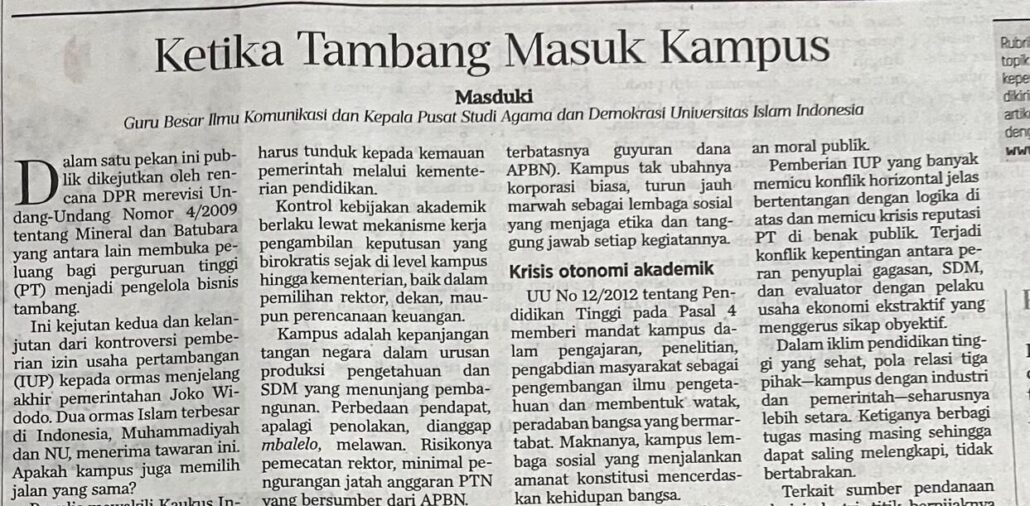Opini oleh: Masduki, Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII
Terbit di Kompas, 30 Januari 2025
Pendirian dan keberlanjutan perguruan tinggi jadi tanggung jawab negara dan masyarakat, dalam pembiayaannya harus menjaga marwah kampus sebagai rujukan moral publik.
Dalam satu pekan ini publik dikejutkan oleh rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang antara lain membuka peluang bagi perguruan tinggi (PT) menjadi pengelola bisnis tambang.
Ini kejutan kedua dan kelanjutan dari kontroversi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas menjelang akhir pemerintahan Joko Widodo. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, menerima tawaran ini. Apakah kampus juga memilih jalan yang sama?
Penulis mewakili Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) berpendapat, gagasan pemberian IUP kepada PT adalah sesat pikir kebijakan negara (Kompas, 20/1/2025).
Korporatisasi PT
Dalam artikel ”Higher Education in Indonesia: The Political Economy of Institution” (2023), Andrew Rosser mengidentifikasi dua problem predatoris yang menyebabkan krisis PT di Indonesia.
Pertama, ketatnya kontrol politik atas semua keputusan akademik dan non-akademik di kampus. Kedua, manajemen internal yang birokratis. Keduanya warisan Orde Baru dalam pengelolaan kampus. Tujuannya, penundukan sivitas akademika agar selaras dengan politik monoloyalitas pembangunanisme Soeharto.
Meminjam Gramsci, di era Orde Baru, kampus adalah ideological state apparatus yang harus tunduk kepada kemauan pemerintah melalui kementerian pendidikan.
“Kampus seperti lembaga politik, organisasi politik, alat mobilitas politik bagi para dosen atau sebaliknya.”
Kontrol kebijakan akademik berlaku lewat mekanisme kerja pengambilan keputusan yang birokratis sejak di level kampus hingga kementerian, baik dalam pemilihan rektor, dekan, maupun perencanaan keuangan.
Kampus adalah kepanjangan tangan negara dalam urusan produksi pengetahuan dan SDM yang menunjang pembangunan. Perbedaan pendapat, apalagi penolakan, dianggap mbalelo, melawan. Risikonya pemecatan rektor, minimal pengurangan jatah anggaran PTN yang bersumber dari APBN.
Intinya, kampus seperti lembaga politik, organisasi politik, alat mobilitas politik bagi para dosen atau sebaliknya. Dalam konteks ini, kita menjadi paham mengapa suara para rektor PTN cenderung seragam untuk setuju, atau minimal diam, atas rencana pemberian IUP, yang jelas berisiko tinggi bagi reputasi kampus di mata publik.
Anehnya, pascareformasi 1998, kondisi tersebut berlanjut di era Jokowi dan Prabowo. Hal itu berkelindan dengan agenda neoliberalisasi dalam bentuk korporatisasi kampus. Jargon kampus mandiri, merdeka secara ekonomi, lebih kuat. Maknanya: harus mencari uang sendiri dan negara lepas tangan.
Dalam hubungan ini, rencana pemberian IUP dikerangka dalam wacana yang sempit dan pragmatis: tambang akan menjawab kesulitan ekonomi di PT (dahaga anggaran operasional kampus yang tak terpenuhi oleh terbatasnya guyuran dana APBN). Kampus tak ubahnya korporasi biasa, turun jauh marwah sebagai lembaga sosial yang menjaga etika dan tanggung jawab setiap kegiatannya.
Krisis otonomi akademik
UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 4 memberi mandat kampus dalam pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan membentuk watak, peradaban bangsa yang bermartabat. Maknanya, kampus lembaga sosial yang menjalankan amanat konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sejak pemerintahan Orde Baru, PT terus mengalami represi secara sistemik, ketika menjalankan peran sosial di atas. Merujuk EJ Perry (2019) dalam Educated-acquiescence, represi atau koersi dapat bersifat negatif seperti pemecatan akademisi yang kritis, pelarangan diskusi akademik, atau bersifat positif (positive coercion), seperti pemberian remunerasi dan ”peluang/tugas” jabatan birokrasi serta unit usaha.
Tujuannya sama: menghambat laju pencapaian akademik dan otonomi akademia sebagai kritikus atas kekuasaan yang koruptif. Proyek merdeka belajar kampus merdeka, link & match, hingga IUP adalah bagian dari skenario ini, yang kerap tidak disadari para dosen.
Pendirian dan keberlanjutan PT adalah tanggung jawab negara dan masyarakat dan dalam pembiayaannya harus menjaga marwah kampus sebagai rujukan moral publik.
Pemberian IUP yang banyak memicu konflik horizontal jelas bertentangan dengan logika di atas dan memicu krisis reputasi PT di benak publik. Terjadi konflik kepentingan antara peran penyuplai gagasan, SDM, dan evaluator dengan pelaku usaha ekonomi ekstraktif yang menggerus sikap obyektif.
Dalam iklim pendidikan tinggi yang sehat, pola relasi tiga pihak—kampus dengan industri dan pemerintah—seharusnya lebih setara. Ketiganya berbagi tugas masing masing sehingga dapat saling melengkapi, tidak bertabrakan.
Terkait sumber pendanaan dari industri, titik berpijaknya adalah mandat atas tanggung jawab sosial industri ke masyarakat lewat PT yang harus terus diperkuat, bukan penerjunan PT sebagai pelaku, pemilik bisnis berskala besar itu sendiri.
Penting disadari bahwa otonomi PT hanya bisa dirawat lewat fokus kerja sivitas akademikanya pada pelayanan akademik, bukan sambilan setelah mengelola industri tambang atau unit usaha komersial lain.
Akhirnya, jawaban atas krisis keuangan PT belakangan ini harus dikembalikan kepada komitmen alokasi APBN untuk pendidikan, dan evaluasi menyeluruh kinerja kampus sebagai lembaga sosial.
Antara lain untuk menjaga stabilitas dan kualitas, jumlah PT yang terlampau banyak (peringkat kedua di dunia setelah India) dapat ditinjau ulang agar dukungan pendanaan publik ke kampus menjadi lebih rasional.