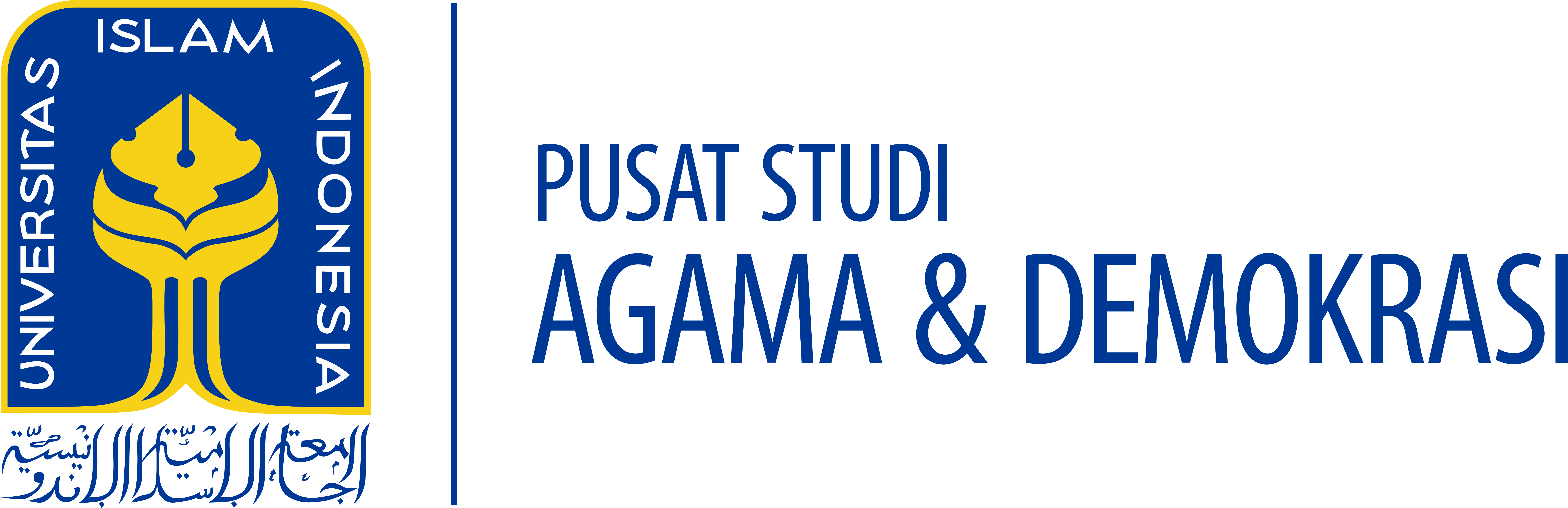Opini oleh: Fathul Wahid, Pembina Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII
Terbit di Kompas, 23 September 2024
Kampus adalah rumah para intelektual yang dituntut untuk turut serta memikirkan kondisi republik.
Dalam sejarah Republik, kampus pernah menjadi penjuru moral. Kaum intelektual lantang menyuarakan kebenaran di tengah hiruk-pikuk kekuasaan. Namun, kini, kampus membisu ketika penyalahgunaan kekuasaan terjadi dalam banyak aspek penyelenggaraan negara.
Beragam kritik telah dialamatkan kepada kaum intelektual di kampus. Mereka dianggap masa bodoh ketika berbagai penyalahgunaan kekuasaan terjadi secara terang benderang. Tak jarang, praktik ini dikemas dengan peraturan yang mengesankan keabsahan praktik kekuasaan yang brutal.
Publik merindukan kaum intelektual yang bersuara kritis. Kampus sebagai lokomotif utama masyarakat sipil jadi salah satu tumpuan harapan publik.
Suara moral yang kritis dari berbagai organisasi keagamaan pun mulai parau. Pelbagai fakta di lapangan menghadirkan cerita yang memprihatinkan.
“Studi-studi terbaru tentang demokrasi Indonesia menunjukkan bukan saja aspek kemunduran demokrasi, melainkan juga otoritarianisme yang bercorak populis.”
Tidak banyak kampus yang bersuara jernih dan kritis. Apa yang terjadi pada 22 Agustus 2024, ketika banyak warga kampus bersama elemen masyarakat sipil lain turun ke jalan menolak revisi Undang-Undang Pilkada, memang sedikit menjadi pengobat rindu. Namun, sebagian besar kampus masih tenggelam dalam kebisuan.
Mengapa kampus menjadi masa bodoh dan bahkan apatis? Proses dialog dan interaksi personal dengan banyak pemimpin kampus menghasilkan penjelasan awal.
Termasuk di dalamnya adalah ketiadaan kesadaran akan tanggung jawab, eksposur kepada informasi yang terbatas, kompas moral yang rusak, dan kemerdekaan intelektual yang terenggut. Penjelasan ini bersifat bertingkat.
Bukan urusan kampus
Sikap apatis bisa dijelaskan karena sebagian menganggap bersuara kritis saat ada pelanggaran bukan tanggung jawab kampus. Kesadaran akan tanggung jawab kampus sebagai penjuru moral bangsa tidak tumbuh dengan baik.
Kampus sudah terlalu sibuk dengan urusan domestik. Energi warga kampus sudah terkuras, untuk beragam aktivitas kejar setoran guna memenuhi banyak indikator capaian, baik individual maupun institusional. Aktivitas ini terkadang penuh cucuran keringat, tetapi minim manfaat bagi kampus.
Atau jangan-jangan memang hal itu disengaja, untuk menguras energi, sehingga kampus dan warganya tidak lagi sempat berpikir dan bersuara kritis? Jika ini benar, aktivisme intelektual kampus dimatikan dengan sistematis dan masif tanpa banyak disadari di kalangan intelektual.
Di tengah situasi yang memprihatinkan ini, saatnya petinggi dan warga kampus perlu meningkatkan literasi akan tanggung jawabnya dari sumber otoritatif yang variatif. Salah satunya terkait dengan tanggung jawab intelektual publik. Kampus adalah rumah para intelektual ini yang dituntut untuk turut serta memikirkan kondisi republik.
Eksposur informasi
Kalaupun kesadaran akan tanggung jawab intelektual masih ada, keterbatasan eksposur ke informasi belum mampu memantik kampus untuk bersuara.
Informasi terkait dengan pelanggaran yang sampai ke media sering kali sudah tersaring. Potret terkait pelanggaran pun menjadi kabur. Hal ini ditambah dengan narasi tandingan yang sengaja disebar di ruang publik, termasuk dengan melibatkan para pendengung dan warganet yang terkecoh.
Untuk itu, petinggi dan warga kampus perlu keberanian untuk membuka diri terhadap keberagaman informasi. Hanya dengan demikian, kampus tidak seperti katak di dalam tempurung yang abai dengan perkembangan mutakhir di sekitarnya. Pergaulan pun perlu diperluas supaya tidak terjebak pada kamar gema, yang kalis dari wacana alternatif.
“Kampus sebagai lokomotif utama masyarakat sipil jadi salah satu tumpuan harapan publik.”
Kebenaran tak ditentukan oleh frekuensi paparan informasi yang kita dengar, tonton, atau baca. Kebenaran kadang tersembunyi di dalam informasi yang jarang kita akses karena kanal penyebarannya sering kali dipersempit. Eksposur yang baik terhadap informasi valid akan sangat berperan dalam memantik dan merawat kesadaran yang ujungnya adalah kemauan untuk bersuara.
Kompas moral
Bisa jadi akses informasi sudah baik, tetapi kampus tetap saja diam seribu bahasa. Mengapa demikian? Penjelasan lainnya adalah kompas moral kampus yang soak. Kompas moral yang seperti ini perlu dikalibrasi karena tidak lagi sensitif mendeteksi dan menunjukkan arah dengan benar.
Medan magnet di sekitar kompas moral sudah diganggu. Salah satu caranya adalah dengan sebaran narasi publik yang disetir atau bahkan dimanipulasi oleh para autokrat informasi (Guriev dan Treisman, 2019).
Pelanggaran telah dinormalisasi dengan peraturan yang dalam perumusannya disuntik dengan beragam kepentingan. Demokrasi dikatakan masih baik-baik saja dengan bermacam-macam dalih meski kenyataannya jauh dari itu.
Studi-studi terbaru tentang demokrasi Indonesia menunjukkan bukan saja aspek kemunduran demokrasi, melainkan juga otoritarianisme yang bercorak populis. Logika publik dipermainkan. Kebenaran pun menjadi samar dan sengaja dihancurkan supaya publik mengalami kekaburan dalam melihat kebenaran.
Efek dari operasi ini bisa sangat mengerikan karena kampus bisa saling bersitegang dalam mencari kesepakatan di era pascakebenaran.
Kampus mer(d)eka
Jika kompas moral masih bekerja tetapi kampus tetap tidak bersikap, penjelasan lain dapat diberikan.
Kampus tidak merdeka karena beragam sebab. Sebagian kampus tergantung kepada sumber daya negara dalam operasinya. Hal ini menjadikannya tidak bebas bersuara karena risiko yang bakal mendera. Bahkan, sampai hari ini, kampus dengan ratusan profesor pun masih belum diberi hak secara merdeka memilih pemimpinnya. Tangan kekuasaan pemerintah masih mencengkeram kuat, baik secara terbuka, samar, maupun tersembunyi.
Akibatnya, pemimpin kampus yang terpilih pun tersandera politik utang budi. Suara yang tidak sejalan dengan penguasa, meski jernih, hanya akan tebersit di dalam hati atau tersendat di kerongkongan.
Di sini keberanian kampus untuk bersuara perlu ditumbuhkan dan dikondisikan. Kebebasan akademik tidak sekadar menjadi slogan. Program kampus merdeka yang dalam beberapa tahun terakhir menyita perhatian sama sekali tidak menyentuh aspek ini.
Merdeka hanya sebatas jargon di tengah cengkeraman tangan kekuasaan yang halus dan terbukti membunuh kemerdekaan intelektual.
Bayangkan, mayoritas kaum intelektual di kampus mengalami ketakutan dan kekhawatiran untuk—meminjam pesan salah satu pendiri Universitas Islam Indonesia, Bung Hatta—mengatakan kesalahan kepada penguasa.
Tentu, tanggung jawab moral ini tidak lantas menjadi alasan kampus abai dari kewajiban lainnya, seperti pengajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Kewarasan kampus harus tetap dijaga dengan semestinya. Jika tidak, kampus merdeka akan berubah menjadi kampus mereka.