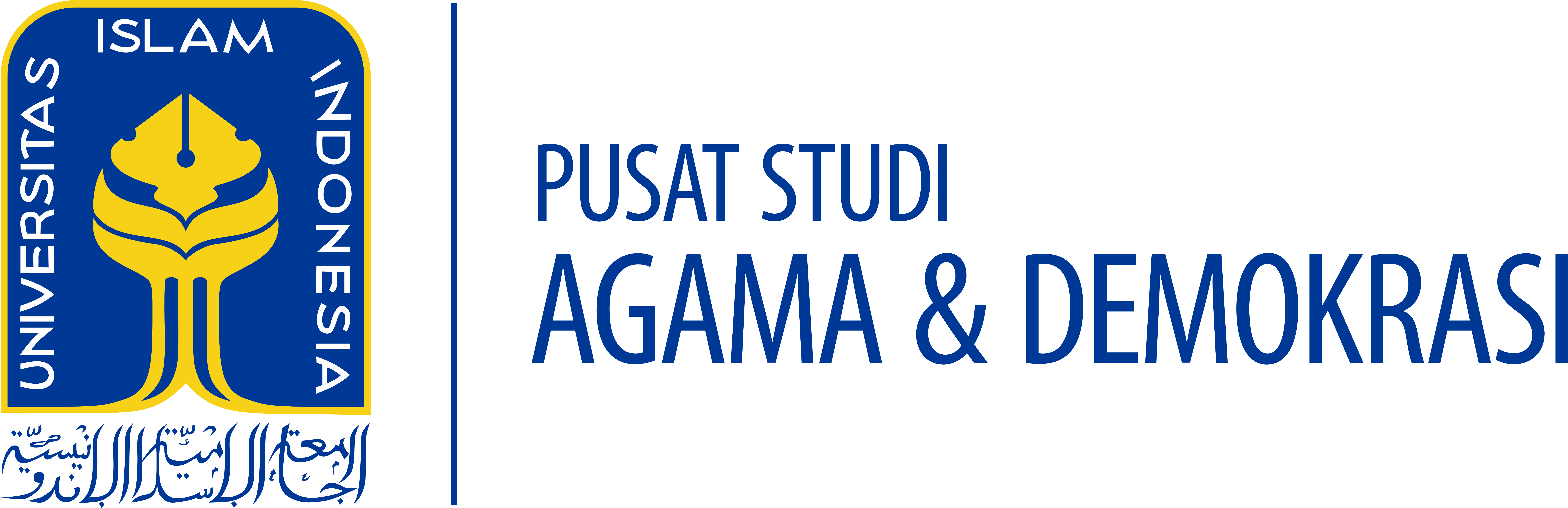Opini oleh: Masduki, Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII
Terbit di Kompas, 11 Juli 2025
Ada 13 perguruan tinggi (PT) besar di Indonesia masuk kategori buruk (”red flag”), berisiko buruk (”high risk”), dan dalam pemantauan (”watch list”).
Laporan indeks integritas akademik (Research Integrity Risk Index/RI2) yang dibuat Profesor Lokman Meho dari American University of Beirut bulan ini mengguncang dunia akademik kita.
Laporan ini menyebut ada 13 perguruan tinggi (PT) besar di Indonesia masuk kategori buruk (red flag), berisiko buruk (high risk), dan dalam pemantauan (watch list). Kejutan muncul karena di dalamnya banyak perguruan tinggi negeri (PTN) langganan ’ranking dunia’. Misalnya UI, UGM, dan Unair yang selalu masuk ranking pemeringkat PT global seperti Times Higher Education Supplement (THES), QS, dan Webometrics.
Beragam respons muncul dari asosiasi seperti Forum Rektor Indonesia dan pemerintah. Namun, tak ada bantahan bahwa integritas akademik universitas memang bermasalah.
RI2 adalah yang pertama di dunia yang mengukur risiko integritas riset berbasis data empiris dari kanal penerbit ilmiah. Indeks ini mengukur dua aspek, yaitu R-Rate atau jumlah artikel yang ditarik (retracted) per 1.000 publikasi dan D-Rate atau persentase artikel yang dihapus dari database pengindeks (terutama Scopus/WoS).
Masuknya 13 PT kita dalam RI2 bukan berarti semua dosennya tak berintegritas karena indeks ini mengukur kualitas institusional, bukan individual.
Publikasi indeks ini, apa pun dan bagaimanapun metodenya, menampar muka PTN pemburu peringkat atau status bereputasi secara umum. Ia sekaligus membuka aib bahwa pemeringkatan yang selama ini fokus ke jumlah publikasi dan sitasi penuh kepalsuan tak selalu berhubungan dengan integritas dan komitmen ke nilai-nilai dan budaya akademik yang sehat.
Produktivitas tinggi dalam karya ilmiah kita yang terindeks dan diklaim tertinggi di Asia Tenggara sejak 2022 tak berhubungan dengan kualitas publikasi. Indeks Meho menunjukkan ada lingkaran mafia yang melawan akal sehat akademis: adanya jurnal abal-abal, diikuti pemeringkatan abal-abal, dan diamplifikasi oleh publikasi statistik peringkat abal-abal.
Bersama publikasi indeks Meho, muncul berita dua guru besar terlibat praktik plagiasi mahasiswa bimbingannya di UIN Makassar. Ada indikasi kuat, para guru besar abai melakukan supervisi langsung proses menulis mahasiswanya, turut terjebak mengejar angka publikasi dengan menekan mahasiswa bimbingan yang karena minim pengetahuan dan sikap etis, memilih jalan pintas.
Siapa patut disalahkan? Menunjuk mahasiswa bimbingan sebagai pelaku utama, menyederhanakan masalah. Tahun 2024, dunia akademik terguncang dugaan plagiasi publikasi, pencatutan, dan terbitan di jurnal predator yang melibatkan salah satu guru besar yang juga dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional.
Krisis integritas akademik ibarat fenomena gunung es, terjadi tak hanya di 13 PT ini.
Mitos integritas akademik
Publikasi hasil indeks menunjukkan tiga hal. Pertama, tata kelola akademik di tingkat institusi PT yang buruk. Hampir pasti semua PTN/PTS kita memiliki dokumen integritas akademik, tetapi proses pelaksanaan dan evaluasi/audit tak pernah dilakukan dengan baik.
Dokumen integritas hanya sekadar produk administrasi dan marketing gimmick untuk membangun imaji publik terkait reputasi. Integritas didekati sebagai tugas administrasi, indeksasi numerik, bukan keilmuan (scientific approach).
Kedua, secara khusus sistem evaluasi dan kontrol kelembagaan atas publikasi yang dihasilkan akademisi, termasuk guru besar, tak berorientasi ke mutu dan mengalami falsifikasi.
Ketiga, kerja publikasi ilmiah terjebak kerja-kerja mafia, anti-sains, dan menggambarkan kepanikan akademis (panic academia) untuk sekadar memenuhi tuntutan karier, bukan kerja akademis. Ada problem sistemik-struktural yang tak hanya berskala individu, di level universitas, tetapi kebijakan pemerintah menyangkut standardisasi PT.
Sejumlah pertanyaan muncul untuk para elite PT yang masuk daftar indeks: apakah telah ada mekanisme audit publikasi? Sudahkah dilakukan mitigasi ketat atas praktik plagiasi dan pengiriman artikel ke jurnal predator? Apakah dosen yang bekerja dan mahasiswa yang akan lulus hanya dikejar target publikasi, atau memperoleh pembimbingan untuk menulis artikel yang beretika?
Apakah sistem penilaian capaian akademik dosen mendorong riset dan publikasi yang bermakna atau hanya sebagai syarat formal? Di era PT yang mengalami liberalisasi, marketisasi; integritas institusi seperti kejujuran, komitmen ke nilai-nilai ilmiah dan tanggung jawab sosial akademik, jadi mitos.
Integritas adalah diksi pemasaran, dikemas dengan menunjukkan angka-angka capaian statistikal untuk target ekonomis: jumlah mahasiswa yang menjadi sumber klasik pendapatan dan keberlanjutan.
Komitmen integritas akademik tersandera kepentingan kelembagaan jangka pendek meraih reputasi semu sebagai universitas berkelas dunia, atau kepentingan individu elite kampus untuk menjaga karier/jabatan struktural akademik.
Belajar dari heboh indeks Meho, mendesak dilakukan audit integritas akademik oleh otoritas independen yang dibentuk menteri atau lembaga akreditasi mandiri. Ini bagian dari penjaminan mutu dan indikator keberlanjutan universitas sebagai lembaga sosial bermartabat.
Permendikbudristek No 39/2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah perlu ditinjau dengan menegaskan kewajiban audit integritas atas karya ilmiah oleh PT, apalagi merespons jumlah artikel yang melonjak akibat penetrasi teknologi akal imitasi. PT jangan hanya suka memanfaatkan produktivitas dosen (di hilir), tetapi abai memitigasi (hulu), supervisi, dan audit.