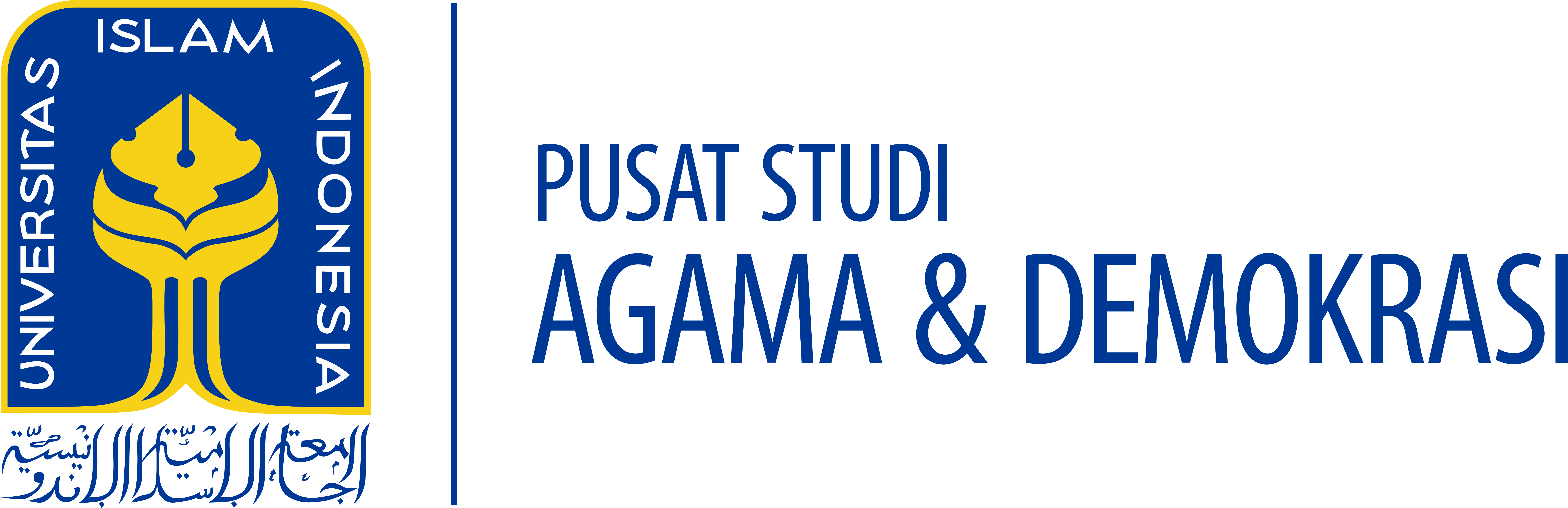Opini oleh: Masduki, Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII
Terbit di Kompas, 22 Desember 2023
Artikel Supriadi Rustad berjudul ”Pemecatan Profesor” (Kompas, 28/11/2023) memicu kembali perdebatan tentang posisi dan relevansi jabatan guru besar atau profesor di dunia akademik di Indonesia. Rustad mencatat hanya dalam beberapa bulan, satu profesor tetap dipecat oleh menteri dan tiga profesor kehormatan menjadi terdakwa.
Rustad menawarkan solusi struktural peninjauan Permendikbudristek No 38/2021, yang di antaranya mengatur tentang profesor kehormatan, demi menjaga marwah perguruan tinggi. Tulisan ini mencoba melihat lebih jauh problematika ekonomi politik gelar profesor.
Memahami guru besar
Kata ”besar” dalam ”guru besar” sebetulnya adalah inti sari dari pencapaian karier akademis tertinggi ini. Maknanya, besar amanah dan besarnya harapan publik akan kiprah scholarship, kontribusi akademis yang paripurna, bukan kontribusi politik dan ekonomi.
Amanah ini tentu hampir mustahil dapat dipenuhi oleh para birokrat atau politisi yang memperoleh gelar guru besar.
Alih-alih, mereka justru memperburuk reputasi kampus melalui perilaku yang nirmoral publik. Dengan kata lain, guru besar bukan persoalan ”milik/menjadi orang besar”, apalagi sekadar bergaji besar. Ini tanggung jawab akademik besar. Ia refleksi pencapaian akademik (academic achievement) yang telah mendapat apresiasi secara nasional hingga global.
Dalam kerangka ini, ada baiknya jika seorang profesor tak perlu disapa dengan sebutan Prof secara berlebihan di ruang publik. Sebutan itu cukup tertulis dalam dokumen.
“Dengan kata lain, guru besar bukan persoalan ’milik/menjadi orang besar’, apalagi sekadar bergaji besar. Ini tanggung jawab akademik besar.”
Dalam konteks tata kelola perguruan tinggi, keberadaan guru besar menjadi sangat penting karena ia mendongkrak marwah institusi produsen pengetahuan ini di satu sisi. Sementara, mengikuti tradisi liberalisme pendidikan, ia akan meningkatkan daya tawar terhadap pasar mahasiswa, alumni, dan menunjang peningkatan status akreditasi internasional.
Patut disayangkan, aksi ”pacuan kuda” percepatan profesor di berbagai perguruan tinggi dimotivasi oleh ambisi nilai pasar ekonomis ini, bukan penguatan kinerja akademis semata.
Guru besar adalah pengawal tiga keteladanan publik sekaligus: teladan dalam produksi karya, rujukan disiplin etis dalam publikasi, dan figur panutan dalam relasi sosial. Mereka diharapkan menjadi sosok yang digambarkan filsuf Antonio Gramsci sebagai ”intelektual organik”, figur yang mengombinasikan kerja intelektual akademis di dalam kampus dengan kerja lapangan, aktivisme sosial dan digital untuk perubahan sosial di luar pagar kampus.
Para ilmuwan ini menempatkan ilmu sebagai amunisi, kearifan jiwa sebagai kompas, sikap kritis dan advokasi sosial sebagai pola kerja. Mereka bukan kelompok elite, melainkan bagian dari kawula alit, gaya hidupnya cenderung asketik, mudah menyentuh hati publik.
Dalam budaya akademik yang sehat, guru merupakan sosok teladan dalam aktivitas mengajar, meneliti, dan publikasi. Besar itu berarti tugasnya/mandatnya paripurna.
Apabila ”guru kecil” tugasnya berjalan kaki, guru besar seharusnya berlari. Selaras dengan ini, merujuk pada struktur jabatan fungsional kampus, jika seorang asisten ahli boleh berjalan santai, mandat jabatan lektor adalah berjalan dengan lebih terpola.
Sementara itu, pemegang jabatan lektor kepala (LK) dituntut melakukan lari maraton, dan akhirnya seorang profesor wajib membuat laku sprint, jalan cepat, memimpin di garis depan. Jangan sampai terjadi fenomena terbalik: para profesor justru hidupnya santai, ”pensiun”. Guru besar adalah ruang akademik baru yang lebih kuat, bukan tujuan akhir perjalanan akademik.
Kompleksitas jabatan profesor
Iklim akademik perguruan tinggi di Indonesia yang mengalami krisis melahirkan tiga model profesor yang saling bertolak belakang. Pertama, profesor berbasis lompatan akademik luar biasa, dengan puluhan hingga ratusan karya publikasi akademik yang konsisten dengan bidang ilmunya, bisa diakses oleh publik, dan lain-lain. Mereka berproses secara alamiah dan jabatan profesor hanya bonus.
Kedua, profesor yang lahir dari praktik politisasi, transaksi politik akademik melalui gelar profesor kehormatan. Jejak akademiknya minimal bahkan tidak ada. Ketiga, profesor yang lahir ”cepat saji” lewat beragam program percepatan, kursus singkat menulis, dan pendampingan.
“Iklim akademik perguruan tinggi di Indonesia yang mengalami krisis melahirkan tiga model profesor yang saling bertolak belakang.”
Kategori pertama akan berkontribusi pada peningkatan jumlah ilmuwan, penguatan disiplin keilmuan yang memperkuat reputasi perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan. Kategori kedua, justru berkontribusi memperkeruh reputasi kampus dari lembaga akademik menjadi lembaga politik.
Kategori ketiga, jumlahnya semakin meningkat, melahirkan budaya akademik instan yang berlanjut setelah menjadi profesor. Kiprah profesor akselerasi ini ibarat makanan cepat saji: ada tetapi ”kurang bergizi”.
Problem lain muncul ketika budaya akademik di Indonesia mengaburkan makna dan tugas profesional dosen dengan birokrat kampus-pemerintahan, dianggap saling menunjang.
Status profesor menjadi alat mobilitas sosial vertikal, feodalisasi, dan perilaku sosial anomali di mana seorang guru besar bergaya hidup priayi. Profesor juga kerap kali dianggap sebagai puncak karier dan para penerimanya merasa sudah ”pensiun” dari dunia akademik, berpindah ke dunia politik, menjadi birokrat kampus, dan sebagainya. Belakangan bahkan terjadi inflasi, menyusul beberapa profesor terindikasi korupsi dan kolusi.
Pendek kata, kondisi ini berlawanan dengan apa yang digagas Humboldt di Universitas Berlin tahun 1800-an ketika universitas memiliki academic freedom dari tekanan politik dan industri dalam riset dan pengajaran. Menjadi profesor justru sebuah identitas sosial yang harus selalu disebut dalam pergaulan non-akademis.
Profesor kerap kali jadi alat mobilitas politik vertikal, bukan sebagai ruang keterlibatan sosial secara horizontal. Lebih jauh, terjadi komodifikasi-marketisasi, di mana gelar ini dipergunakan untuk mencari proyek, membuat lembaga kursus cepat dalam publikasi paper, dan meraih jenjang karier akademik.
Dalam beberapa tahun ini, jamak juga terjadi politisasi atas gelar profesor melalui praktik pemberian gelar kepada tokoh politik atau pengusaha yang disertai transaksi pengaruh atau transaksi sumber daya ekonomi antara pemberi dan penerima.
Maraknya fenomena ini dan program akselerasi/jalan pintas menuju profesor tanpa rekam jejak akademik menjadi contoh kelindan antara intervensi negara yang terlalu kuat pada rezim administrasi akademik, kuasa uang, dan krisis identitas intelektual kampus di Indonesia. Terdapat indikasi berlanjutnya persepsi buruk warisan Orde Baru terkait peran dan posisi perguruan tinggi sebagai agen pemerintah, subsistem birokrasi pemerintah yang korup.
Berangkat dari situasi ini, perubahan Permendikbudristek terkait jabatan profesor harus diikuti dengan pengembalian otonomi akademik perguruan tinggi, pemisahan yang jelas antara profesi di ruang akademik dan struktur politik. Selain itu, peningkatan produksi pengetahuan yang berlandaskan komitmen bahwa jabatan fungsional profesor adalah hasil kerja akademik panjang sebagai ilmuwan tertentu, bukan kerja teknis administrasi akademik.