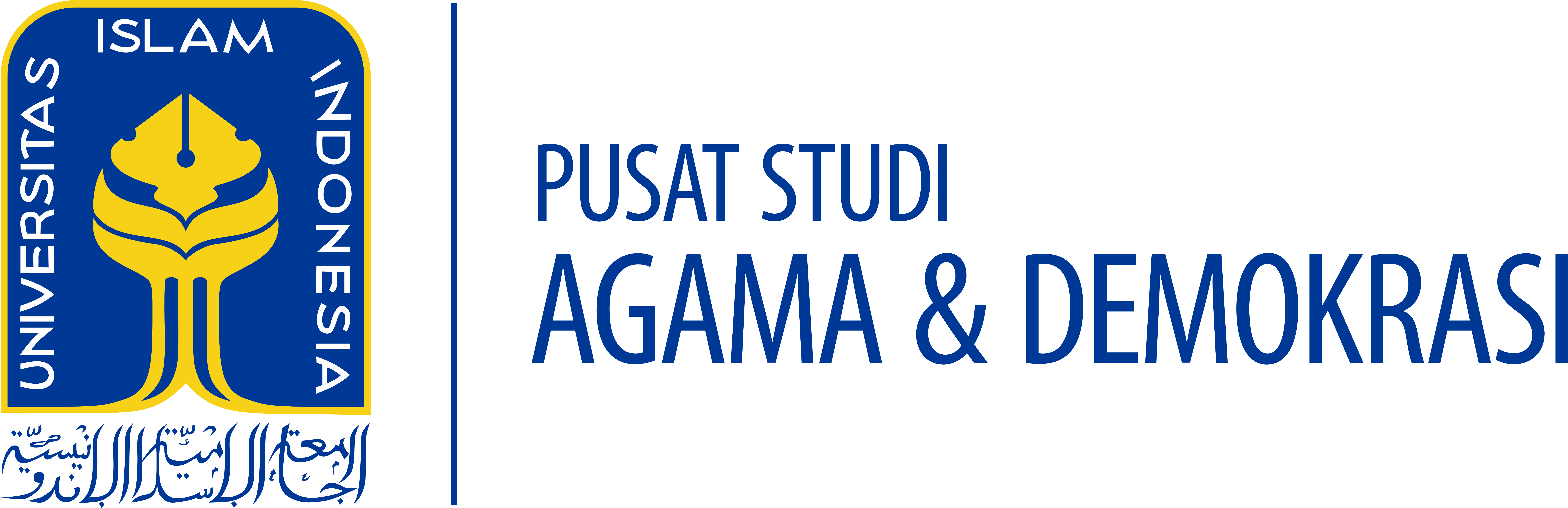Opini oleh: Despan Heryansyah, Sekretaris PSAD UII Terbit di Kompas, 12 Februari 2025
Kasus yang menimpa I Wayan Agus Suartama (IWAS) atau Agus, seorang penyandang disabilitas tanpa tangan di Mataram menyita perhatian publik dan diberitakan hampir setiap hari di media cetak maupun elektronik. Bagaimana mungkin, seorang pria yang tidak memiliki tangan, dapat menjadi pelaku pelecehan seksual dan dijerat dengan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terhadap puluhan perempuan yang mengaku sebagai korbannya. Di luar itu, yang menarik adalah bagaimana proses hukum dilakukan terhadap Agus oleh pihak yang berwenang, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Pemasyarakatan. Bagaimana menerjemahkan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum?
Perspektif Sosial dan Akomodasi yang Layak
Melihat kasus Agus, publik, termasuk juga instrumen penegakan hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan petugas Lapas, masih rancu dalam menerjemahkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses hukum. Ada yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara istimewa atau dispesialkan dari pelaku tindak pidana lainnya. Ada pula yang berpandangan bahwa seorang penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum seharusnya tidak diproses secara pidana, kondisi disabilitasnya dijadikan sebagai alasan pemaaf atas tinda pidana yang dilakukannya. Ada juga yang berpandangan bahwa penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, tidak perlu mendapat perhatian, biasa saja sebagaimana yang lainnya. Semua anggapan di atas adalah tidak tepat, penyandang disabilitas tidak perlu diperlakukan Istimewa atau dispesialkan karena justeru akan menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana lainnya, penyandang disabilitas juga tidak boleh dilepaskan dari tuntutan pidana karena kondisi disabilitasnya semata, terutama disabilitas fisik, ia harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana mestinya.
Lalu, bagaimana memperlakukan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum? Dalam konteks proses, penyandang disabilitas atau siapapun harus diperlakukan sama, tidak boleh ada pembedaan. Namun, instansi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan, harus memastikan bahwa semua hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam proses peradilan tersebut, harus dihilangkan. Misalnya, jika ada penyandang disabilitas tuli-bisu, maka dengan alasan berdasarkan undang-undang dia juga bisa ditangkap dan ditahan, namun proses penangkapan dan penahanannya harus menghilangkan hambatan komunikasi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut, misalnya dengan menghadirkan juru bahasa isyarat. Begitu seterusnya dalam proses yang lain. Penyandang disabilitas yang mengunakan kursi roda misalnya, boleh ditangkap dan ditahan, bahkan harus jika itu menurut perintah hukum, namun polisi harus memastikan dikantor polisi saat proses BAP, pengguna kursi roda dapat bergerak dengan mudah kemanapun ia mau. Coba bayangkan misalnya, apparat penegak hukum menahan seorang pengguna kursi roda, namun di Rutan tidak ada kamar hunian yang memiliki closed duduk, bagaimana seorang pengguna kursi roda dapat memenuhi hajatnya?
Kebutuhan Regulasi ke Depan
Dari aspek regulasi jaminan hak penyandang disabilitas, sebetulnya Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang sangat lengkap. Ada UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), lalu ada UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, lalu di level yang lebih konkret ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Hanya saja, dalam aspek yang lebih teknis, belum ada peraturan yang lebih lanjut terutama di level Kepolisian dan Mahkamah Agung. Polri belum ada peraturan teknis tentang bagaimana menerjemahkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam tugas dan fungsi kepolisian. Begitupun dengan Mahkamah Agung, belum ada peraturan yang lebih detil menerjemahkannya dalam kewenangan hakim dan pengadilan. Diskusi mengenai pemenuhan akomodasi yang layak melalui peraturan internal, baik di Kepolisian RI maupun MA RI, sebetulnya sudah dimulai dan berulang kali dilakukan. Namun masih tarik-ulur karena perbedaan persepektif dan pemahaman yang belum merata dalam memahami paradigma disabilitas.
Kasus Agus, sejatinya menghenyak kita bersama dan menjadi kesadaran bersama bahwa peraturan internal yang lebih teknis, bahka sampai ke level SOP sangatlah dibutuhkan. Agus tidak hanya sendiri, ada banyak Agus lain di Indonesia, seorang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, yang mengharuskan instansi penegak hukum melayaninya. Dalam catatan penulis, berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan, ada 1.092 penyandang disabilitas di Indonesia yang tengah berada di Rutan maupun Lapas. Artinya angkanya tidaklah sedikit. Dengan peraturan internal dan SOP yang jelas, maka POLRI, Jaksa, maupun Hakim tidak lagi akan kesulitan dan kebingungan jika menghadapi kasus serupa. Selain itu, justeru akan melindungi anggota yang bertugas karena bertindak berdasarkan SOP yang tersedia. Dalam kasus agus, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun Lapas, beruntung karena dengan pendampingan yang tepat dari jaringan masyarakat sipil, tidak terjadi kesalahan tindakan maupun pelayanan yang cukup serius. Pada level ini, kita harus mengapresiasi petugas yang bekerja di lapangan.